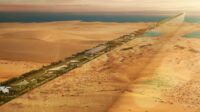Penetapan Soeharto—Presiden RI kedua sekaligus mantan mertua Presiden Prabowo Subianto—sebagai pahlawan nasional memicu diskusi luas di berbagai lapisan masyarakat. Media mainstream, podcast, hingga lini masa media sosial ramai membahas keputusan ini. Topik tersebut menjadi bahan obrolan, mulai dari diskusi serius di kalangan elit politik dan pengamat, hingga percakapan ringan masyarakat di kedai kopi.
Pembahasan ini kembali membelah Indonesia menjadi dua kubu: mereka yang setuju dengan mempertimbangkan jasa-jasa Soeharto, dan mereka yang menolak karena melihat rekam jejak kelam yang menyisakan luka panjang.
Bagi sebagian elit maupun masyarakat yang tidak bersinggungan langsung dengan politik, Soeharto dianggap layak menerima gelar pahlawan nasional. Namun bagi kelompok yang hidup di wilayah abu-abu politik—lawan politik, pers, korban pelanggaran HAM, hingga keluarga yang masih menuntut keadilan—gelar tersebut dinilai tidak layak.
Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat ini dijamin Undang-Undang, sebuah hak yang baru kembali dirasakan setelah tumbangnya rezim Soeharto pada 28 Oktober 1998. Saat itu, masyarakat merayakan berakhirnya era pembungkaman selama 32 tahun Orde Baru.
Mengurai Jejak yang Membelah Bangsa
Sesuai judul artikel “Soeharto: Rekam Jejak yang Membelah Bangsa”, tulisan ini memaparkan rekam jejak sang Smiling General—baik jasa maupun dosa-dosanya—yang hingga kini membuat bangsa terpecah dalam menyikapi gelar pahlawan nasional tersebut.
Jejak Jasa Besar Soeharto
Nama Soeharto telah tercatat dalam sejarah Indonesia, baik sebelum maupun sesudah ia menjabat sebagai presiden. Salah satu jasanya yang sering diangkat adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, momen penting dalam Agresi Militer Belanda II. Serangan tersebut memiliki dampak besar secara militer, politik, dan psikologis di tingkat internasional. Soeharto berperan dalam mengatur strategi serta memimpin pergerakan pasukan, membuat namanya mulai dikenal.
Setelah peristiwa G30S, Soeharto juga berperan dalam menstabilkan situasi politik nasional. Puncak kontribusinya terlihat ketika ia menjabat sebagai Presiden RI ke-2. Ia membenahi fondasi ekonomi Indonesia yang kala itu terpuruk dengan menggandeng para teknokrat—dikenal sebagai Mafia Berkeley—dan menjalankan kebijakan ekonomi yang stabil, seperti menurunkan inflasi yang hampir mencapai 600%, memperbaiki keuangan negara, serta menarik investasi asing.
Melalui program Pelita dan Repelita, pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran: pembangunan jalan, waduk, jembatan, irigasi, sekolah, puskesmas, serta industri dasar seperti pupuk, baja, dan energi.
Program Keluarga Berencana berhasil menekan angka kelahiran. Ribuan SD Inpres dibangun. Pada era keemasannya (1970–1990-an), ekonomi Indonesia tumbuh pesat, angka kemiskinan menurun, dan pembangunan merata.
Dosa-Dosa Soeharto
Untuk mencapai stabilitas demi pembangunan ekonomi, Soeharto menempuh jalan yang dinilai sangat mahal: rakyat membayar dengan nyawa, kebebasan, dan ketakutan. Dosa tersebut bukanlah dosa kecil, melainkan catatan kelam yang membekas dalam sejarah bangsa.
Tangan kekuasaan Soeharto dinilai berlumuran darah. Ia tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan korupsi besar-besaran.
Pelanggaran besar pertama terjadi pasca-G30S, berupa pembunuhan massal, penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, dan pembuangan terhadap mereka yang dituduh terlibat PKI. Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban, menjadikan peristiwa tersebut salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di Asia abad ke-20.
Pelanggaran HAM lainnya turut terjadi dalam penanganan konflik di berbagai daerah, seperti Timor Timur (termasuk Tragedi Santa Cruz 1991), Talangsari (1989), Tanjung Priok (1984), Aceh, dan Papua saat status DOM diterapkan.
Kebebasan berpendapat dibatasi. Media massa diawasi ketat, kritik dibungkam, dan beberapa media—seperti Majalah Tempo—pernah dibredel karena memberitakan hal yang tidak disukai rezim. Banyak aktivis, oposisi, dan tahanan politik ditangkap tanpa proses hukum.
Dosa besar lainnya adalah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Transparency International pernah menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar dolar. Sektor-sektor vital dikuasai yayasan keluarga dan para kroninya, membuat ekonomi Indonesia rapuh dan sangat bergantung pada kekuasaan.
Akhir kekuasaan Soeharto terjadi ketika rakyat tidak lagi mampu menahan tekanan. Krisis moneter memperparah situasi. Gelombang demonstrasi merebak di seluruh Indonesia. Untuk meredam aksi, kekuasaan kembali menggunakan pendekatan kekerasan. Terjadi penculikan aktivis dan mahasiswa, intimidasi, serta kekerasan yang menimpa para demonstran—berujung pada tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II. Banyak mahasiswa tewas, sementara sebagian lainnya hilang hingga kini tanpa jejak.
Setelah Soeharto jatuh, keluarga korban tidak berhenti menuntut keadilan. Aksi Kamisan terus digelar setiap Kamis di depan Istana Merdeka sejak 2007. Aksi tersebut telah melewati 847 kali pertemuan, namun keadilan belum juga datang.
Layakkah Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional?
Melihat jasa dan dosa Soeharto, muncul pertanyaan besar: apakah ia layak diberi gelar pahlawan nasional?
Secara ideal, seorang pahlawan nasional seharusnya tidak memiliki rekam jejak pelanggaran kemanusiaan yang besar. Hal itu bertentangan dengan norma dan rasa keadilan publik. Cukuplah Soeharto dikenang sebagai Bapak Pembangunan, gelar yang sesuai dengan jasanya.
Namun sebagai pahlawan nasional? Rakyat berhak terbelah dalam pendapat.
(KA)