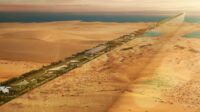JAKARTA – Roti sourdough, roti fermentasi alami yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, kini menjelma menjadi simbol gaya hidup sehat dan autentik di era modern. Dari dapur artisan hingga lini media sosial, roti ini dipuja karena keaslian proses pembuatannya yang “alami” dan cita rasa khasnya. Namun di balik remah sempurna dan aroma asamnya yang menggoda, tersimpan cerita lain: antara kesabaran dan kecepatan, antara otentisitas dan komersialisasi.
Tren sourdough meledak saat pandemi Covid-19 melanda. Ketika ragi instan langka, jutaan orang di seluruh dunia mulai membuat starter alami, campuran tepung dan air yang menumbuhkan koloni mikroba aktif. Merawat starter ini memberi banyak orang rasa tenang di tengah ketidakpastian — semacam terapi sederhana di dapur.
Dari situ, komunitas home baker bermunculan. Mereka berbagi resep, kegagalan, dan keberhasilan di media sosial. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadikan sourdough sebagai fenomena visual: video tentang starter berbuih, adonan yang mengembang, hingga seni mengukir permukaan roti atau scoring menjadi tren global. Sourdough bukan lagi sekadar makanan, tapi karya estetika yang bisa dijual.
Namun di balik keindahan itu, muncul pertanyaan soal keaslian. Popularitas yang tinggi membuat banyak toko roti tergoda mengambil jalan pintas. Proses fermentasi alami yang seharusnya memakan waktu 24–48 jam diganti dengan tambahan zat asam buatan untuk meniru rasa khas sourdough. Hasilnya: roti yang tampak serupa, tetapi kehilangan manfaat dan “jiwa” proses alaminya.
Artisan baker seperti Aston Adiwijaya dari Bake Bros atau Roti Macan Bandung mengaku terus berjuang mempertahankan integritas proses fermentasi sejati. Namun, di tengah permintaan pasar yang terus naik, menjaga starter hidup dalam skala besar bukan hal mudah.
“Menjaga kualitas itu seperti menjaga makhluk hidup. Tidak bisa instan. Tapi pasar sekarang maunya cepat,” ujar Aston.
Padahal, daya tarik utama sourdough tidak hanya pada tampilannya, melainkan pada sains di baliknya. Fermentasi alami membuat roti ini lebih mudah dicerna, memiliki indeks glikemik rendah, serta berfungsi sebagai prebiotik yang baik bagi pencernaan. Klaim kesehatan inilah yang membuat banyak konsumen rela membayar mahal, bahkan setelah tren pandemi mereda.
Kini, sourdough menjadi cermin budaya makan modern: masyarakat ingin yang alami, tetapi tetap instan; mengagungkan proses lambat, asal hasilnya cepat dijual.
Pertanyaannya pun muncul — apakah kita masih bisa membedakan mana roti yang benar-benar hidup, dan mana yang hanya meniru rasanya?